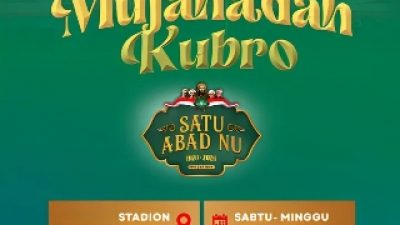Oleh: Dahlan Iskan
Inilah dua orang yang tahu kapan harus berhenti jadi wartawan. Dua-duanya kini jadi profesor-doktor.
Satu di Universitas Airlangga, Surabaya. Satunya lagi Universitas Brawijaya, Malang. Yang satu sudah agak lama (Desember 2024), satunya lagi besok: Prof Dr Prija Djatmika. Rabu 11 Februari 2026.
Imron Mawardi (Amang), yang lebih dulu jadi guru besar, kini menjabat wakil dekan di Unair. Prija Djatmika sudah lama muter ke mana-mana: dipakai jadi saksi ahli di Mabes Polri, Polda-Polda, Kejaksaan sampai ke persidangan di pengadilan.
“Orang itu, kalau berprestasi di satu bidang, cenderung tetap berprestasi –ketika pindah ke bidang yang lain”.
Anda masih ingat siapa yang beberapa kali mengatakan itu. Pun Imron dan Prija. Keduanya sangat berprestasi sebagai wartawan. Tetap berprestasi di kampus masing-masing.
Betapa menyesal keduanya kalau mereka tetap bertahan sebagai wartawan –pun dengan alasan idealisme dan cinta profesi.
Saat Imron naik pangkat menjadi redaktur ekonomi di Jawa Pos, saya memberinya modal Rp 100 juta –cukup besar saat itu. Dengan uang itu saya minta Imron bermain saham. Beneran. Di bursa efek Indonesia.
Syaratnya hanya satu: diskusikan dengan semua wartawan ekonomi yang jadi anak buahnya. Yakni saham mana yang harus dibeli. Kapan harus dijual untuk dibelikan saham lagi.
Saya ingin wartawan ekonomi tidak hanya menulis tentang saham tapi juga mengerti seluk beluk permainan di dalamnya. Mempraktikkannya.
Semua keputusan saya serahkan sepenuhnya kepada Imron. Tidak perlu minta izin. Misalkan rugi tidak apa-apa. Ludes pun tidak masalah: itu seperti uang kuliah.
Tentu saya mengucapkan semua itu dalam hati. Ternyata beneran. Saya lupa menanyakan kelanjutannya. Pun sampai saya dan Imron meninggalkan Jawa Pos.
Demikian juga waktu saya membeli Jaguar atau pun Mercy S500. Secara bergilir wartawan saya minta mencoba mengemudikannya. Setidaknya ikut naik di dalamnya: itu juga kuliah kerja nyata.
“Bagaimana kalau menabrak?”
“Tidak apa-apa. Ini kan diasuransikan,” jawab saya selalu.
Sebenarnya saya sudah cukup ”gigih” merayu Prija: agar tetap bekerja di JP. Artinya: tinggalkan pekerjaan dosen di UB. Ia sudah tujuh tahun bekerja di Jawa Pos. Sudah meliput banyak peristiwa besar. Sudah menjadi pemred mingguan Gugat di bawah koordinasi Imawan Mashuri. Sudah sering ditugaskan ke luar negeri. Sudah beberapa kali diinterogasi aparat hukum dan keamanan soal kerasnya isi tulisannya.
Saya tawari Prija uang Rp 30 juta. Tapi pinjaman. Untuk beli rumah. Ia menolak. Ia mau kalau bukan pinjaman. Tapi tidak mungkin diberikan begitu saja: ”tidak ada pintu administrasi” untuk pengeluaran seperti itu. Padahal sudah saya bilang: boleh dikembalikan kapan saja dengan cara apa saja.
Tapi reaktor UB waktu itu, Prof Dr Zainal Arifin, punya tawaran lebih menarik. Prija akan disekolahkan sampai S-3. Prija menyerah ke UB. Dan itu terbukti merupakan keputusannya yang sangat tepat. Kalau ia tetap di Jawa Pos saya bisa menangisinya sekarang.
Selama di Jawa Pos, Prija memang bisa membeli rumah terkecil dari yang ada: tipe 36. Dengan cara mencicil. Lunas. Lalu beli lagi rumah kedua: dua kali lebih besar. Rumah itu ia pertahankan sebagai catatan dalam hidup dan karirnya.
Waktu Amang dikukuhkan sebagai guru besar, saya tidak bisa hadir: sedang di negara manca. Pun saat Prija dikukuhkan Rabu besok.
Dari keputusan Prija memilih berhenti jadi wartawan itu saya berpikir panjang. Masa depan terbaik wartawan adalah jadi dosen. Maka saya membuat keputusan: wartawan yang sudah bekerja lima tahun saya minta melanjutkan kuliah S-2. Dengan biaya sendiri. Setelah lulus, semua biayanya diganti Jawa Pos. Anda tahu apa maksud keputusan seperti itu: pelit terarah.
Dengan punya ijazah S-2, wartawan bisa melamar menjadi dosen. Tugasnya sebagai wartawan dialihkan ke generasi yang lebih muda. Kerja wartawan perlu fisik yang muda. Tapi akan dikemanakan wartawan senior sungguh tidak mudah. Maka menyiapkannya menjadi dosen tidaklah mahal.
Tentu dengan persyaratan dosen yang baru, beasiswa S-2 tidak cukup lagi. Harus S-3. Itu pun kalau putusan lama itu masih berlaku.
Waktu memutuskan pilih berhenti dari wartawan itu, usia Prija masih 36-an. Benar-benar umur yang pas untuk banting stir terakhir kali.
Ia tahu penghasilan di Jawa Pos lebih besar –saat itu. Tapi ia bukan orang yang mata duitan. Hidupnya sudah biasa susah. Sejak kecil. Sejak di Madiun. Ia sekolah SD masih tanpa sandal-sepatu. Itu tidak merisaukannya –karena teman sekelasnya juga banyak yang seperti itu.
Ia masih mengalami pulang sekolah cari kayu bakar karena ibunya memasak di pawonan dengan sumber energi kayu bakar.
Dengan latar belakang wartawan ketika menjadi dosen hukum di FH UB, Prija tidak hanya mengajarkan teori dari buku teks. Ia sudah menyaksikan praktik hukum sehari-hari: di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan.
Ilmu yang didapat selama tujuh tahun sebagai wartawan seharusnya setara dengan doktor –minus metodologi dan sistematika.
Pekan lalu, 3 Februari, juga ada wartawan yang jadi guru besar: Prof Dr Dudi Iskandar. Ia berhenti jadi wartawan (Koran Jakarta, Media Indonesia, Berita Satu) setelah 10 tahun malang melintang di jurnalisme. Ia tidak takut kehilangan pekerjaan karena sudah miskin sejak kecil. Bapaknya TKI di Arab, ibunya TKW di Malaysia. Hartanya saat berhenti jadi wartawan hanya sepeda motor yang belum selesai cicilan –dengan istri dan dua anak balita menunggunya di rumah. Ia tabah godaan material demi melanjutkan kuliah. Bagi Dudi ”miskin dan kaya itu keadaan, sederhana itu sikap hidup”.
Judul pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Budi Luhur Jakarta itu seksi: Jurnalisme Plastik. Itulah perjalanan terkini jurnalisme setelah era konvensional, modern, dan post modern: jurnalisme plastik.
Kembali ke Prija. Saya masih sering bertemu Prija. Penampilannya masih tidak banyak berbeda. Pun gaya semangat bicaranya. Tampilan Prija lebih mirip orang perjuangan. Itu dipengaruhi latar belakang kewartawannya. Juga latar belakang tempatnya magang yang panjang: di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya.
Seperti juga LBH-nya Adnan Buyung Nasution di Jakarta, LBH Surabaya diisi oleh para aktivis pergerakan. Tokoh legendarisnya masih ada saat ini: Prof Dr Mohamad Zahidun. Ia kawin dengan teman sepergerakan saya tercantik se-Kaltim: Syahriah Usman.
Saat di LBH itulah Prija kenal dan sering bicara dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional: Buyung Nasution, HC Pricen, Mochtar Lubis, dan Todung Mulya Lubis. Ilmu dan jiwa perjuangan mereka ikut mengalir ke Prija.
Tempat magang mahasiswa sangat menentukan pembentukan karakter setelah lulus nantinya. Karena itu memilih tempat magang harus dipikirkan: karakter seperti apa yang akan menulari jiwanya kelak. LBH saat itu punya nama yang sangat harum: lambang perjuangan penegakan hukum dan keadilan –termasuk demokrasi di dalamnya.
Di awal magangnya itu Prija hanya bertugas menjadi tukang kliping. Tiap hari ia menggunting koran yang menulis kasus-kasus hukum. Kliping itu ia edarkan ke semua pengacara LBH. Prija sudah rajin membaca sejak kuliah: di perpustakaan Unair. Menjadi tukang kliping hanya kelanjutan dari kegemarannya membaca.
Dengan hilangnya koran sekarang ini saya tidak tahu bagaimana para magangis bekerja. Bagaimana cara kliping berita model online. Dulu berita kredibel atau tidak ditentukan oleh koran. Kini begitu sulit menyaring mana berita yang kredibel dan mana yang seolah kredibel.
Sudah banyak doktor dan guru besar hukum –Prija terbukti bisa menunjukkan bahwa ia bukan guru besar biasa-biasa saja.(Dahlan Iskan)