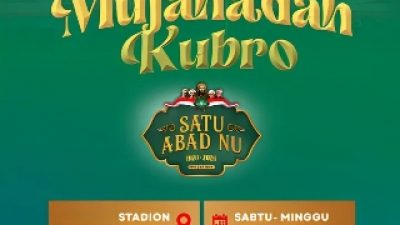Oleh Dahlan Iskan
DI TIONGKOK harga obat ini USD 280. Di Amerika menjadi USD 8.900. Beda 30 kali lipat. Obatnya sama. Penemuan baru. Untuk kanker. Penemunya sama: tim dokter dari RS Sun Yat Sen, Tiongkok. Kegunaannya sama: obat kanker tanpa harus disertai kemo.
Temuan itu baru saja mendapat persetujuan badan obat dan makanan Amerika Serikat, FDA: 9 November lalu. Berarti bulan ini sudah bisa dipasarkan di Amerika. Dengan harga langit Amerika.
Meski menjadi begitu mahal tapi, menurut media di Amerika, masih 20 persen lebih murah dari obat bikinan Amerika: Keytruda. Itu obat terlaris di bidang tersebut saat ini di sana.
Nama obat baru itu: toripalimab. Di Amerika akan dipasarkan dengan nama Loqtorzi. Dengan harga 30 kali lipat tadi.
Uji klinis untuk menemukan obat itu dilakukan selama 2 tahun. Sejak 2018. Awalnya riset dilakukan di rumah sakit kanker Sun Yat Sen, dekat Guangzhou. Hasil riset itu baru saja dimuat di Journal of the American Medical Association (JAMA). Selasa lalu.
”Itu obat bekerja sebagai antibodi monoklonal dengan target PDL-1, Programmed death ligand protein,” ujar Prof Dr Agung Putra, pendiri Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Semarang.
”Dengan obat itu sel kanker tidak bisa melakukan screening sistem imun kita. Dengan demikian imun sistem kita tidak lumpuh oleh serangan kanker,” katanya.
Dr Agung adalah peneliti sel yang sangat intens. Setelah jadi dokter ia tidak mau ambil spesialis. Ia tidak mau jadi dokter klinis. Prof Agung ingin fokus menjadi peneliti. Ia ke Kanada. Mendalami sel di sana.
Pulang dari Kanada Prof Agung mendirikan pusat riset kanker dan stem cell. Ia jual seluruh hartanya: beli tanah murah 6 hektare di pinggiran Semarang. To be or not to be.
Ia dirikan lab kelas dunia. Sudah jadi. Saya sudah ke sana empat kali. Ia bangun hotel tikus. Sudah jadi. Ia semai bibit-bibit tanaman herbal terkait kanker. Sudah berbiak. Mulai keladi tikus sampai butrowali.
Kini bagian lain tanah di selatan Semarang itu lagi diratakan: siap-siap mulai membangun rumah sakit.
Prof Agung ingin membuat mini Mayo Hospital di Semarang: yakni rumah sakit yang terkait langsung dengan pusat riset.
Tadi malam saya meneleponnya. Khusus untuk memahami penemuan baru obat kanker di Tiongkok itu.
Prof Agung sudah meneliti penggunaan kemo dalam penyembuhan kanker.
”Kemo hanya membunuh anak-anak kanker. Tidak bisa membunuh sel induk kanker,” ujarnya.
Itulah sebabnya orang yang sudah dikemo dan sudah dinyatakan bersih kadang masih muncul lagi kankernya.
Di lab SCCR, Prof Agung bisa melihat ”tentara” yang dihasilkan obat kemo itu. Ketika mendekati anak-anak kanker ”tentara” itu membesar. Lalu mampu memakan sel-sel anak kanker yang ukurannya lebih kecil.
”Tapi begitu mendekati sel induk kanker, tentara-tentara kemo itu mengempis. Tidak mampu memakan sel induk kanker,” katanya.
Prof Agung lahir di Lampung. Orang asli Lampung. Istrinya seorang dokter dari Malang.
Dokter Agung lulusan Undip dan tanggal 14 Desember nanti meraih guru besar dari Universitas Sultan Agung.
Awalnya saya tidak percaya ada dokter senekat dr Agung. Hanya mau melakukan riset. Dia mencintai riset. Secara mandiri pula.
Prof Agung termasuk ahli yang anti terapi kemo. Tapi sebelum menemukan penggantinya ia tidak mau menunjukkan sikap antinya.
Yang ditemukan di Tiongkok itu adalah obat kanker tanpa disertai kemo.
”Kami di SCCR juga mengembangkan yang tidak pakai kemo. Kami mengembangkan immunotherapy menggunakan pendekatan isolasi dan culture-engineering CTL (Cytotoxic T lymphocyte). Masih kami lakukan dalam lab,” katanya.
Di Tiongkok obat baru tersebut sudah lebih dulu disetujui untuk digunakan. Sejak enam bulan lalu: Mei 2023. Itu setelah dilakukan 12 kali tahapan uji klinis yang melibatkan 1.200 pasien di berbagai negara di dunia. Termasuk di Singapura dan Taiwan. Hasilnya pun efektif.
Di Tiongkok harga obat memang bisa murah. Di sana harga obat mengacu pada patokan harga yang dipakai di sistem asuransi kesehatan nasional. Sejenis BPJS di Indonesia.
Tidak boleh ada harga obat di atas itu. Tidak ada pasar obat yang terganggu: 95 persen rakyat Tiongkok masuk dalam sistem kesehatan nasional.
Di Amerika harga obat diputuskan semata berdasar daya beli masyarakat. Patokannya: sepanjang orang masih mampu membelinya. ”Bahkan tidak ada hubungan antara penetapan harga obat dengan biaya riset,” tulis media di sana.
Sudah lama saya ingin menulis kiprah riset Prof Agung. Ia masih keberatan. Ia khawatir keinginannya membangun pusat riset terganggu oleh hal-hal di luar ilmu pengetahuan. Sikap emosional dari berbagai pihak bisa mengganggu riset. Baik di birokrasi maupun di lingkungan dokter sendiri.
Saya pun setuju. Jangan sampai energi Prof Agung habis terkuras sia-sia. Apalagi kalau perusuh Disway ikut di dalamnya. (Dahlan Iskan)