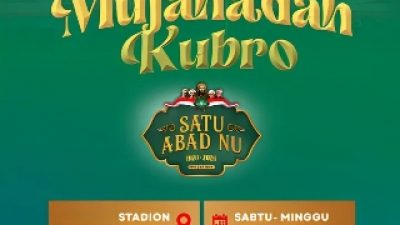Oleh: Dahlan Iskan
Saya berpisah lagi dengan istri: di Makkah. Hampir selalu begitu. Setelah menemani ibadah umrah saya harus pergi ke negara lain.
Kali ini ke negara yang dekat tapi belum pernah saya kunjungi: Yaman. Tetangga selatan Saudi Arabia.
Saya berpesan kepada anggota rombongan yang akan meneruskan menemani istri. Terutama mengenai sakitnyi. Apa yang harus diperbuat kalau penyakit itu datang padanyi.
Mereka masih beberapa hari lagi di Makkah. Mereka tidak panik. Terutama kalau melihat istri saya sedang menggigil hebat. Biasanya pukul empat atau lima sore.
Itu tidak ada hubungannya dengan operasi lutut. Mungkin perasaan istri mengatakan masih ada hubungannya. Tapi saya yakinkan bahwa sakit akibat operasi lututnyi sudah sembuh.
Memang selama di Makkah dan di Madinah, dia tetap pilih pakai kursi roda. Tapi itu lebih karena agar tidak kelelahan.–
Tentu ada konsekuensinya. Pakai kursi roda di saat tawaf –ritual mengelilingi Kakbah tujuh kali– ada tempatnya tersendiri. Tidak bisa di dekat Kakbah. Harus di lantai dua Masjid Al Haram.
Berarti saya juga ikut tawaf di lantai dua. Sebenarnya saya ingin mendorong sendiri kursi roda itu. Tapi peraturan tidak mengizinkan. Yang mendorong harus petugas besertifikat. Saya hanya mengikuti di samping atau di belakang kursi roda.
“Dari mana, Mbak?” tanya saya kepada petugas.
“Dari Lombok”.
“Lombok mana?”
“Lombok tengah”.
“Praya?”
“Kok tahu”.
Dia sudah lima tahun tinggal di Makkah. Ayahnyi bekerja sebagai petani di desa itu.
“Kursinya baru ya?” kata saya melihat kursi yang kinclong itu.
“Iya. Baru beli”.
“Bagus sekali. Ini mercy-nya kursi roda. Biasanya istri saya dapat yang Avanza”.
“Terima kasih. Saya dapat dari orang Singapura. Beliau beli kursi baru. Ketika pulang ditinggal untuk saya”.
Saya beruntung dapat pendorong wanita. Jalannya cepat tapi tidak sampai seperti lari. Saya bisa mengikutinyi dengan jalan cepat yang normal.
Sebenarnya enak tawaf di dekat Kakbah. Lingkarannya kecil. Di lantai dua ini lingkarannya besar. Satu putaran terasa sangat lama. Saya pun tergoda untuk menghitungnya: satu putaran berapa langkah. Agar hitungan itu benar saya menghentikan bacaan doa di putaran kedua: konsentrasi untuk menghitung langkah.
976 langkah.
Anda tidak bisa mengoreksi angka yang saya tulis itu. Hanya saya sendiri yang tahu –mungkin kurang atau lebihnya hanya beberapa saja: terutama kalau perjalanan roda itu lagi macet saking banyaknya yang ingin ngebut.
Berarti 976 kali tujuh putaran: sekitar 7.000 langkah. Masih ditambah hilir mudik tujuh kali saat sa’i: antara Shafa dan Marwah. Sekitar itu juga. Total 15 ribu langkah sekali umrah.
Lega.
Untung kami masuk masjid sebelum waktu magrib. Bisa salat magrib di lantai dua. Bisa pilih lokasi di dekat tempat start tawaf. Istri salat di atas kursi roda. Di kelompok wanita. Saya bersama kelompok para lelaki di bagian depan.
Begitu salat magrib selesai tawaf pun dimulai. Suasananya seperti balap formula one: menyiapkan diri agar bisa start duluan di saat masih banyak orang di jalur lintasan.
Menjelang putaran keenam terdengar azan salat isya. Harus berhenti dulu. Salat isya berjamaah. Lalu berputar lagi untuk menyelesaikan lap keenam dan ketujuh.
Pukul 22.15 ibadah umrah selesai. Lalu ke hotel. Check-in. Ketika tiba dari Madinah tidak sempat check-in. Lebih baik langsung ke masjid dulu. Agar sebelum tengah malam ibadah umrah bisa selesai.
Tentu istri kelelahan –biar pun di kursi roda. Menjelang tengah malam itu saya minta izin untuk mandi sebelum dia. Selesai mandi saya harus ke bandara. Ups…belum bisa ke bandara. Harus mengisi acara live Dismorning: pukul 01.00 waktu Makkah. Atau pukul 05.00 WIB.
Maka selesai mandi saya keluar hotel. Cari lokasi podcast. Cahaya lampu di kamar kurang memadai untuk kamera Redmi termurah ini.
Kebetulan di pinggir jalan menuju masjid Al Haram itu ada tumpukan bata putih. Setinggi satu meter. Ini dia. HP saya letakkan di tumpukan bata itu. Tapi latar belakangnya terlalu terang. Terlalu banyak cahaya di sekitar masjid Al Haram.
Apa boleh buat. Mata pemirsa mungkin agak tersilau oleh cahaya kuat dari berbagai lampu halaman itu.
Kembali ke kamar, ternyata istri belum mandi. Masih kelelahan. Saya pun pamit ke bandara. Ke Yaman.
Sebelum cium keningnyi saya jelaskan sekali lagi kepadanyi: mengapa dia sering menggigil luar biasa.
Biasanya, saat menggigil seperti itu saya taruh telapak tangan saya di keningnyi: normal. Suhu badan tidak naik. Lalu saya perhatikan bahwa dia sudah makan satu jam sebelum menggigil itu: berarti tidak mungkin gula darahnya sedang drop.
“Tenang saja. Menggigil Anda ini tidak bahaya,” kata saya. “Kalau di saat menggigil itu suhu badan Anda naik barulah harus minum obat atau ke dokter”.
Tidak usah khawatir. Jangan minum obat apa pun –agar tidak terjadi salah obat. Itu justru lebih berbahaya. Bisa mengganggu organ lain seperti ginjal.
Lalu dari mana datangnya gigil hebat itu?
Saya sudah bertanya ke banyak dokter. Termasuk dokter saraf. Saya juga membaca banyak literatur tepercaya di internet. Gigil itu bukan atas perintah otak. Kalau gigil itu datang saat suhu badan naik barulah gigil itu atas perintah otak.
Lalu siapa yang memerintahkan gigil itu? Tidak ada. Tidak ada yang memerintahkannya. Itu sejenis gerakan reflek otot akibat kelelahan. Reflek itu datang akibat saraf istri saya yang terganggu oleh gula darah yang tinggi selama puluhan tahun.
Maka saya juga mengoreksi kebiasaan istri –yang ternyata menurut ilmu kedokteran salah: di saat menggigil hebat dia mengambil selimut tebal. Itu tidak boleh. Kalau pun berselimut yang tipis saja.
Begitulah. Teman-teman istri sudah saya beri tahu tentang semua itu. Saya khawatir mereka memberi sembarang obat. Biarkan saja menggigil. Yang terbaik hanya memberi istri minum air hangat. Jangan manis. Lalu pura-pura memijat-mijat punggungnyi. Agar tidak dibilang tidak ada perhatian. Itulah yang juga saya lakukan –biar pun itu bukan jalan keluarnya.
Ada Dewi. Ada Ali Murtadlo dan istri. Ada Bajuri. Ada mas Shodiq dan istri dan anak perempuannya. Semua satu rombongan. Satu grup senam. Semua sudah saya brifing seperti itu. Semua siap menjaga istri selama di Mekah.
“Dalam 30 sampai 60 menit gigil itu akan berhenti sendiri,” kata saya kepada mereka.
Mobil yang membawa saya ke bandara pun tiba. Saatnya saya ke terminal haji Jeddah –di situlah Yemeni Airways berpangkalan. Ini kali pertama saya ke Yaman. Kali pertama naik pesawat Yemeni.
Doa saya satu: jangan ada roket nyasar di penerbangan di atas Yaman yang belum selesai perang ini. Kalau pun ada berikan saya selamat –agar bisa menulis pengalaman itu untuk Disway.(Dahlan Iskan)